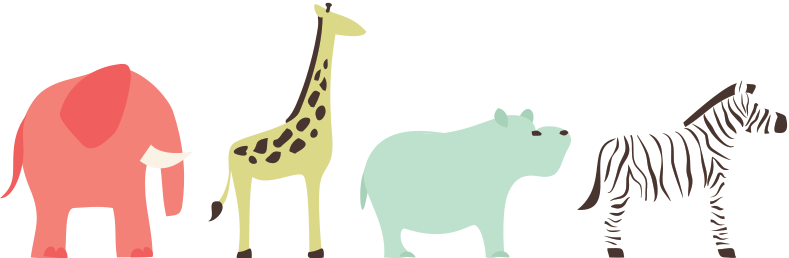Happy reading ❤
“Sometimes the questions are complicated and the answers are simple.”
― Dr. Seuss
“Aku enggak pernah bisa origami. Apalagi bikin burung-burungan kertas. Tapi ini bagus banget. Siapa yang kasih, ya?” kata si bocah perempuan yang menatap origami itu di kamarnya.
“Ayo, makan dulu,” kata pembantu rumah si bocah perempuan sambil membawa senampan makanan. “Kamu sudah bisa bikin origami?” tanyanya.
“Belum, ada yang menaruh ini di tasku. Baik sekali, ya, Bi,” kata si bocah perempuan dengan senang.
Sesudah makan si bocah perempuan lari menuju kamar ibunya. Ia sudah sangat senang menanti kelahiran adik barunya.
“Hai, ini aku kakakmu,” si bocah perempuan bicara kepada perut sang ibu sambil mengelusnya.
“Sudah enggak sabar?” tanya sang ibu.
“Tentu saja, Ma! Aku sangat teramat tidak sabar!” kata si bocah perempuan bersemangat.
“Aku juga mau bicara, aku juga mau,” tiba-tiba adik si bocah perempuan masuk ke kamar ibunya juga.
***
“Kau sudah sangat genius meskipun masih kecil. Kau bisa menyembunyikan identitasmu dengan hal-hal seperti itu pada Valen. Daebak!” kata Karen sambil menyenggol pundak Marc.
“Justru itu kebalikannya Karen,” kata Marc yang suaranya sedikit melemah.
“Maksudnya?” tanya Karen dengan heran.
“Ya, dulu aku anak yang bodoh. Sangat bodoh.”
“Benarkah? Aku tidak percaya.”
“Serius. Aku dulu bodoh banget. Padahal IQ-ku memang di atas rata-rata. Guruku benar, aku hanya belum menggunakan otakku dengan baik pada waktu itu,” curhat Marc.
“Wah, dan sekarang kau sangat mengagumkan. Coba kalau aku enggak suka sama Dani, bisa-bisa aku ikutan gila bersama wanita-wanita di sekolah kita,” kata Karen sambil tertawa kecil.
“Ah, tidak mungkin. Aku ini tetap saja hanya anak biasa.”
“Semenjak pertandingan pertamamu, semua wanita di sekolah tertuju padamu. Hanya saja kau tidak pernah menggubris mereka. Kau tidak genit seperti anak-anak basket lainnya. Contohnya Jorge. Ah, dia enggak jelas sebenarnya niat mau dekat sama Valen atau enggak. Untung Valen juga enggak pernah menggubris dia, sama kayak kamu,” jelas Karen.
“Jangan bilang aku sama kayak dia, ah. Aku sama sekali tidak mau dibandingin sama dia,” kata Marc dengan nada cuek.
“Tapi kamu ‘kan suka sama dia,” balas Karen.
Marc mendengus pelan. “Capek juga, kayaknya percuma.”
“Masa sudah nyerah?”
“Hey, tujuh tahun Karen. Tu-juh!”
“Wow, hebat juga. Emang di Amerika belum pacaran sama sekali?” tanya Karen penasaran.
“Pernah, cuma satu kali,” jawab Marc sambil mengacungkan jari telunjuk kanannya pada Karen.
“Woah,” kali ini Karen benar-benar terkejut. “Biasanya lelaki Amerika banyak pacarnya.”
“Aku ini lelaki Spanyol, bukan Amerika. Oh, iya, kenapa masih pakai kacamata? Biasanya kalau cheerleader enggak pakai. Terus rambutmu…” Marc menatap Karen sebentar lalu melepas ikatan rambut Karen, “… mendingan digerai. Siapa tahu Dani tertarik denganmu.”
“Dia ‘kan sudah pernah melihatku di cheerleaders dengan gaya seperti itu. Sepertinya dia tidak tertarik,” kata Karen sambil tersenyum kecut.
“Ya lanjutin saja. Enggak perlu nunggu jadi cheerleader buat narik hati dia,” kata Marc sambil tersenyum lebar pada Karen. “Pulang, yuk. Mau aku anterin atau gimana?”
“Aku pulang sendiri saja, rumahku dekat banget sama sekolah.”
“Oke, hati-hati, ya. Aku duluan,” pamit Marc.
***
Karena bosan, Valen berjalan-jalan di sekitar koridor sekolah. Ia tertarik dengan salah satu ruangan di sekolahnya, yaitu ruangan musik. Valen membuka perlahan pintu ruangan itu bahkan hampir tanpa suara karena takut ada orang di dalamnya.
Ternyata ia benar, ada seseorang yang sedang duduk di bangku piano sambil menatap piano di depannya, memunggungi Valen. Orang itu mulai mendentingkan tuts piano itu sambil bernyanyi.
And I’d give up forever to touch you
‘Cause I know that you feel me somehow
You’re the closest to heaven that I’ll ever be
And I don’t want to go home right now
And all I can taste is this moment
And all I can breathe is your life
‘Cause sooner or later it’s over
I just don’t wanna miss you tonight
And I don’t want the world to see me
‘Cause I don’t think that they’d understand
When everything’s made to be broken
I just want you to know who I am
Who I am…
Orang itu memainkan pianonya dengan tempo penuh emosi dan tekanan. Piano itu menjadi pelampiasannya saat ini. Valen yang mendengarnya pun terbawa suasana, seakan dentingan piano itu tercipta untuknya, kepada perasaannya.
Seketika orang itu menghentikan permainan pianonya. “Apa yang kau dengar?” tanyanya dingin tanpa menoleh kepada Valen.
“Semuanya,” ucap Valen lemah. Rasanya perasaannya telah dihantam bertubi-tubi oleh lagu itu.
Marc bangun dari kursi pianonya lalu menghampiri Valen. “Kau kenapa? Apa kau sakit?”
Tidak, hanya mini-heart attack, batin Valen. “Ti─tidak, aku tidak apa-apa,” kata Valen sambil merapikan poninya pelan.
Marc semakin berjarak sangat dekat dengan Valen.
“Apa yang kau lakukan?” tanya Valen dengan nada sedikit panik.
Marc menggerakkan telapak tangannya untuk memegang pipi Valen, tapi Valen malah mundur menjauhi Marc.
“Aku mohon, izinkan aku menyentuhmu. Sekali saja,” pinta Marc.
Tak sadar Valen terdiam lalu membiarkan Marc membelai lembut pipinya. Tiba-tiba saja Valen merasa nyaman dengan perlakuan Marc. Perasaan panik yang menjalar di tubuhnya tadi berhasil padam hanya dengan sentuhan dari Marc.
“Terima kasih telah mendengarkan laguku,” kata Marc sambil tersenyum.
“Sudahlah,” Valen melepaskan tangan Marc dari pipinya. “ Aku tidak ingin terlihat Karen, aku tidak mau dia salah paham.”
“Apa?”
“Dia pantas mendapatkanmu.”
“Aku tidak mengerti…”
“Semoga kau bahagia bersamanya─”
“Valen…”
“─dan jangan kecewakan dia, dia wanita yang baik. Kau tidak perlu menyangkalnya. Kalian terlihat serasi. Selamat sore, Marc,” Valen langsung pergi meninggalkan Marc yang dari tadi tak sempat menjelaskan yang sebenarnya.
Marc kembali ke pianonya lalu membanting jari-jarinya yang kekar pada tuts piano itu. “Sampai kapanpun dia tidak akan sadar dan mengerti,” gumam Marc penuh amarah.
***
“Kamu cantik,” kata si bocah laki-laki kepada si bocah perempuan yang sedang tertidur di kelas.
“Aku memang cantik,” tiba-tiba si bocah perempuan menjawab tanpa membuka matanya. Ia bangun, “Ngapain dekat-dekat aku? Sana sana,” usirnya.
“Aku ‘kan enggak apa-apain kamu.”
“Ya pokoknya enggak usah deh dekat-dekat. Satu meter paling sedikit.”
Si bocah laki-laki menggelengkan kepalanya. “Baiklah aku pergi.”
Si bocah perempuan berjalan cepat mendahului si bocah laki-laki, tak disangka si bocah perempuan tersandung tali tas temannya yang ditaruh di lantai. Untungnya, si bocah laki-laki sigap memegang tangan si bocah perempuan sehingga tak terjatuh.
“Kau bisa mematahkan lehermu,” kata si bocah laki-laki sambil menarik si bocah perempuan agar berdiri dengan benar.
“Kau tahu apa?” kata si bocah perempuan ketus. Ia langsung berlalu pergi tanpa mengucapkan terima kasih.
“Aku ini apa coba di mata dia? Ngomong terima kasih aja enggak,” gumam si bocah laki-laki.
***
“Ini bangunnya ‘kan enggak beraturan, kamu bagi-bagi sesuai yang ada rumus luasnya misalnya persegi, segitiga, trapesium. Nah, nanti kalo sudah ketemu hasil-hasilnya tinggal kamu tambah, itu luas seluruhnya. Gampang banget ini. Sudah mau lulus ginian saja masih oon. Lex, Lex.”
“Untuk apa aku punya kakak genius jika tidak bisa aku tanyakan apa-apa? Sudah bagus adikmu ini bertanya,” kata Alex agak ngambek.
“Iya, iya. Sudah cepat kerjakan. Nanti aku periksain,” kata Marc sambil mengacak-acak rambut Alex.
“Aduh, anak Mama pintar-pintar semua. Nih, Mama bikinin brownies,” ujar Mama Roser, ibu Marc dan Alex.
“Kebetulan banget Marc lapar. Thank you, Ma,” lalu Marc langsung mengambil sepotong brownies yang disediakan ibunya.
Tiba-tiba saja bel pintu rumah Marc berbunyi.
“Mama saja yang buka, kalian lanjut belajar,” kata Mama Roser lalu ia berjalan menuju pintu.
“Alex!!! Kamu ngundang teman-temanmu?” teriak Mama Roser dari arah pintu.
“Iya, Ma, suruh masuk saja,” balas Alex dengan teriakan juga.
Lalu segerombolan anak sepantaran Alex memenuhi ruang tamu rumah kediaman Marquez.
“Kalian mau tawuran atau apa?” tanya Marc heran sambil menghitung berapa anak yang datang. Ada tujuh orang, semuanya anak laki-laki.
“Kita mau belajar sama kau, Marc,” kata Alex dengan nada gembira.
“Dasar kau, Alex!!!” jerit Marc.
Akhirnya Marc pasrah. Hitung-hitung membagi ilmu kepada yang lebih muda darinya.
Setelah kira-kira satu setengah jam menjadi guru privat dadakan, tiba-tiba bel pintu rumah Marc berbunyi lagi.
“Ada gelombang duanya?” kata Marc sambil memelototi Alex.
“Apaan? Enggak ada cuma segini doang, Marc.” Alex juga ikut-ikutan memelototi Marc. “Matanya biasa aja, dong.”
Marc menormalkan posisi matanya setelah beradu mata dengan Alex. Dia membuka pintu rumahnya karena tadi ibunya sedang pergi ke rumah nenek Marc.
“Hei, Bro!” sapa Dani dengan senang.
Satu pengacau lagi, pikir Marc. Tapi dia senang sahabatnya bisa ke rumahnya agar ia tidak terkucilkan oleh teman-teman Alex yang tiga tahun di bawahnya. “Ayo, ke kamarku saja,” ajak Marc.
“Woah, kamarmu belum berubah,” seru Dani.
Kamar Marc memang belum di renovasi lagi sejak kepergiannya ke Amerika, bedanya dulu Alex sekamar dengannya. Cat berwarna hijau muda lembut menghiasi dindingnya. Rak kecil yang menggantung di dindingnya, di atasnya terdapat beberapa miniatur motor balap, foto masa kecilnya, bahkan beberapa boneka kecil yaitu boneka kumbang dan teddy bear. Ranjangnya juga ditutupi dengan warna senada dengan tembok kamarnya, ada boneka bugs bunny kesayangan Marc di atasnya. Tak lupa ada televisi dengan layar lumayan besar agar ia dan Alex bisa puas bermain Play Station.
“Ya, aku tidak sempat. Lagian kamar ini tetap nyaman meski tidak di renovasi sama sekali. Bahkan apartemenku yang di Amerika tidak senyaman kamarku sendiri,” kata Marc sambil tertawa.
“Ih, bohong banget,” balas Dani sambil tertawa juga.
“Mau ngapain ke sini? Tumben. Enggak pacaran?” tanya Marc.
“Kau makin sama kayak Valen, ngungkit tentang pacar terus. Kayak kau belum pernah pacaran saja,” jawab Dani dengan suara ngambek.
“Ya aku pernah, tapi enggak membahagiakan.”
“Sama, aku juga Marc. Cuma sayang kalo diputusin.”
“Aduh, bodoh banget sih, Dan? Kasus kita sama, cuma mantanku enggak se-populer Marcia. Tapi ya tetap aja, jangan maulah dibodohin wanita terus. Terkadang wanita bisa lebih jahat dari pada kita,” terang Marc.
“Sayang tapi Marc, aku juga suka banget sama dia.”
“Ya sekedar suka aja ‘kan? Kau cuma sebatas mengagumi dia saja, enggak lebih. Carilah di luar sana. Pasti ada yang jauh lebih baik,” kata Marc sambil menepuk punggung Dani. “Ah, sudah enggak perlu galau, mending kita main PS. Sudah lama kita tidak main bareng.”
***
Si bocah laki-laki sedang duduk di depan piano yang ada di atas panggung auditorium sekolahnya. Ia duduk sendirian, di depannya juga ada kertas-kertas yang berisi sebuah lagu.
“Lirik lagu ini bagus, aku suka,” gumamnya.
Ia mulai mempelajari satu-satu not lagu tersebut sambil mencobanya sedikit-sedikit dengan pianonya.
Ternyata dari kejauhan si bocah perempuan duduk di bangku paling belakang auditorium. Ia mendengar setiap dentingan piano yang si bocah laki-laki mainkan. Mendadak ia merasa nyaman. Padahal lirik lagunya tidak tersirat kebahagiaan yang sepenuhnya.
“Iris, dinyanyikan oleh Goo Goo Dolls, tahun 1998,” gumam si bocah perempuan.
to be continued…
how is it? Thank you yang udah selama ini baca blog aku. I’m really happy and welcome to all of you. Aku berharap juga kalian komen *ngarep banget* but nope, i mean, aku mau tahu siapa aja sih yang rajin baca. Itu aja kok :D. I’m trying hard to make this fiction more better for y’all. Thanks ❤